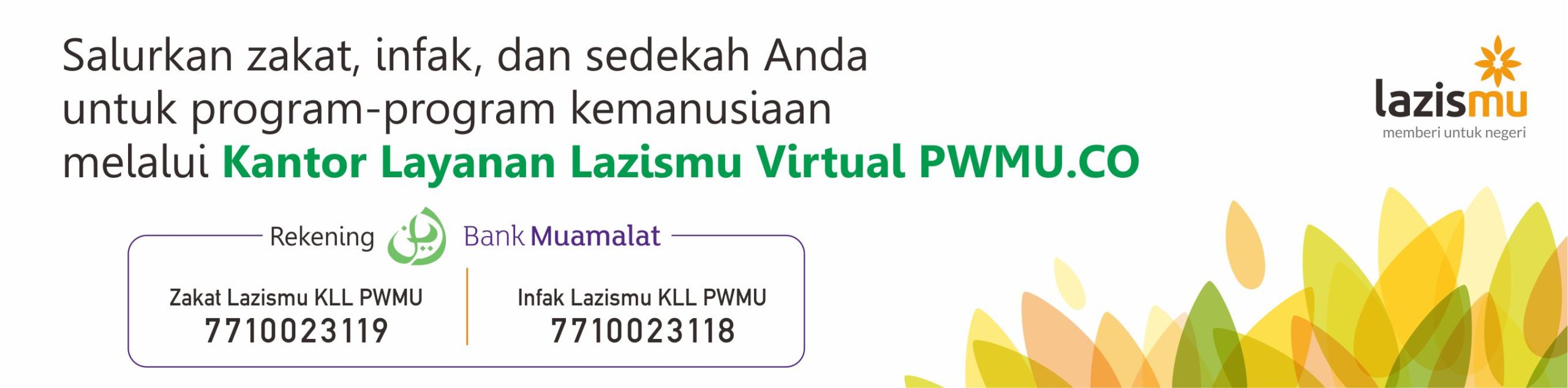Ketaqwaan dan Kesalehan Sosial
Nilai dan Implikasi Ketaqwaan dalam Membentuk Kesalehan Sosial
Tarjihjatim.pwmu.co – Oleh Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. (Guru Besar Sosiologi Agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang) pada Khutbah Idul Fitri di Masjid Manarul Islam, Malang, Senin, 1 Syawal 1446 H-31 Maret 2025 M.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن. قَالَ الله تَعَالَى: يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. وَقَالَ الله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِي
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
Hadirin Rahimakumullah
Setelah memulai ibadah puasa Ramadhan pada 1 Ramadhan 1446 H yang bertepatan dengan 1 Maret 2025 M, pada hari ini, 1 Syawal 1446 H, bertepatan dengan 31 Maret 2025, umat Islam di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia, berbondong-bondong mendatangi tanah lapang dan masjid untuk melaksanakan “amaliah ‘ubudiah muakkadah”, yakni Shalat Idul Fitri sebagai perwujudan dari sikap pengagungan kepada Allah (ta’dhimullah atau taqdisullah) dan tasyakkur atau bersyukur kepada Allah.
Pengagungan kepada Allah terwujud dengan kumandang takbir dan tahmid sejak kemaren petang hingga hari ini, serta Shalat ‘Id secara berjamaah di tanah lapang dan masjid pada pagi ini. Kegiatan secara kolektif (berjamaah) umat Islam sejak 1 Ramadhan hingga pada pagi ini, juga merupakan perwujudan syukur betapa Allah telah menganugerahkan nikmat yang teramat berharga kepada kita berupa kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama sebulan penuh.
Puasa merupakan kewajiban individual bagi umat Islam yang sudah mencapai aqil baligh. Selama bulan Ramadhan kita tidak saja menahan diri dari aktivitas-aktivitas fisik pada siang hari yang membatalkan puasa: minum, makan, dan berhubungan dengan suami-isteri, tetapi juga berupaya menjauhkan hati kita dari aktivitas-aktivitas yang dapat mengurangi kesempurnaan dan bahkan merusak ibadah puasa. Selain itu puasa Ramadhan merupakan “Madrasah Ruhaniah” atau “Sekolah Spiritual” , karena di samping merupakan ibadah fisik, juga merupakan ibadah ruhani yang penuh dengan muatan atau materi, aktivitas, nilai, dan tujuan spiritual, .
Hadirin Rahimakumullah
Selama bulan Ramadhan, kita dengan penuh kesadaran niat berpuasa, melakukan aktivitas ruhani berpantang dari larangan yang berakibat batalnya puasa kita, serta melakukan berbagai aktivitas ibadah baik ibadah regular (wajib) dan ibadah sunnah salah satunya shalat tarawih. Semua aktivitas ini pada dasarnya merupakan aktivitas pendidikan, di mana kita merupakan pihak yang menerima pendidikan atau “mutarabbi”, sementara yang “mendidik” kita, atau sebagai “murabbi” adalah Allah Semua kegiaatan ini berlangsung secara ruhaniah atau spiritual.
Hubungan antara “mutarabbi” dengan “murabbi”, tidak terjadi dalam ruang fisik yang kasat mata seperti di madrasah atau sekolah dalam pengertian konvensional. Karena berlangsung secara ruhani atau spiritual, maka untuk melaksanakan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadhan, meniscayakan keberimanan kepada Allah sebagaima ternyatakan secara eksplisit dalam surat al-Qur’an ayat 183:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibakan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Q.S. al-Baqarah: 183)
Bagi kalangan tertentu, berpantang untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami-isteri pada siang hari, setidaknya selama 13 jam, merupakan larangan yang berat. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, tidak semua orang Islam bersedia melaksanakan puasa Ramadhan maupun kewajiban lainnya. Al-Qur’an teah mengisyaratkan kualitas ketaatan orang Islam terhadap ajaran Islam, sebagaimana dapat dicermati dalam surat Fathir ayat 32 :
فَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ
“Kemudian Kami wariskan Kitab (Al-Qur’an) kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.” (Q.S. Fathir: 32)
Menurut ayat ini, umat Islam merupakan umat yang mewarisi al-Qur’an. Sebagaimana ayat tersebut memberi gambaran bahwa terdapat tiga golongan umat Islam yang menunjukkan keragaman kualitas keberterimaan dan ketaatan kepada ajaran Islam, yaitu: yaitu:
- ظالم لنفسه: Orang yang menzalimi dirinya sendiri, meninggalkan beberapa kewajiban dan melakukan beberapa dosa.
- مقتصد: Orang yang pertengahan dalam ketaatan, melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang haram, tetapi tidak melakukan amalan sunnah.
- سابق بالخيرات بإذن الله: Orang yang berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah, rajin dalam ketaatan, melaksanakan kewajiban dan sunnah, serta menjauhi yang haram dan makruh.
Hadirin Rahimakumullah
Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 183, puasa selama bulan Ramadhan, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai predikat sebagai hamba Allah yang bertakwa. Dengan menyampaikan pandangan ini, seseorang menegaskan bahwa puasa memiliki nilai instrumental yang bertujuan mengembangkan kesadaran dalam beragama. Puasa, seperti ibadah lainnya, bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kondisi keberagamaan yang ideal, yaitu takwa. Penegasan ini penting karena sebagian orang mungkin memahami kewajiban ibadah hanya sebagai formalitas, sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Ibadah yang sebatas formalitas, menurut pandangan tokoh Sufi, seperti Ibnu Athaillah, tak ubahnya seperti kurangka. Lengkapnya, “Amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamya.”
الأعمالُ صُوَرٌ قائِمَةٌ وَأَرْوَاحُهَا وُجُودُ سِرِّ الْإِخْلَاصِ فِيهَا
Al-Qur’an menyebut konsep kunci etik-spiritual, yaitu takwa, lebih dari dua ratus kali. Setiap kali menghadiri shalat Jumat, kita mendengar pengingat tentang pentingnya menjaga kualitas ketakwaan. Khatib sering membacakan salah satu ayat yang menegaskan hal ini, yaitu ayat 102.
يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (QS. Āli ‘Imrān: 102)
Seruan yang disampaikan setidaknya setiap pekan pada setiap shalat Jum’at, serta seringnya al-Qur’an menyebut kata taqwa, menjadi petunjuk nyata akan pentingnya taqwa. Meminjam suatu frasa dalam literatur sosiologi, taqwa memiliki makna dan fungsi sebagai “the sacred canopy”, “pelindung suci”. Sebagaimana lazimnya kanopi pada bangunan yang memberikan efek perlindungan dan keindahan, taqwa juga demikian. Taqwa melindungi kita dari godaan dan tekanan untuk melakukan hal yang dilarang Allah, serta membuat kepribadian kita tampak indah melalui kebaikan yang kita wujudkan. Kita harus melalui proses secara bertahap hingga akhirnya membangun “the sacred canopy” berupa takwa dalam diri kita.
Hadirin Rahimakumullah
Untuk memahami proses ini, penting bagi kita menyegarkan kembali pemahaman pengertian terhadap konsep taqwa, di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh al-Imam Zainuddin Hujjah al al-Islam Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali. Dengan merujuk pada al-Qur’an, al-Ghazali dalam Minhajul “Abidin ila al-Jannah, mengemukakan tiga pengertian taqwa, yaitu: (1) al-Khasyyah wa al-Hibah (takut dan segan) kepada Allah; (2) al-Tha’ah wa al-ibadah (taat dan ibadah); (3) Tanzihu al-Qalb ‘an al-Dzunub (penyucian hati dari dosa-dosa).
Taqwa dengan demikian merupakan suatu proses secara gradual yang dimulai dengan munculnya rasa takut dan segan terhadap kekuasaan Allah, yang pada proses berikutnya karena takut dan segan kepada Allah dilanjutkan dengan ketaatan dalam melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadhan. Puncak ketaqwaan pada akhirnya adalah tanzihu al-qalb ‘an al-dzunub (penyucian hati dari dosa-dosa). Inilah taqwa yang sebenar-benarnya (haqqa tukotih) sebagaimana dikemukakan dalam ayat 102 dalam surat al-Imran.
Orang yang bertakwa pada akhirnya mampu menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang termasuk dalam kategori “dosa-dosa hati.” Dalam Bidayah al-Hidayah, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa dosa-dosa hati ini mencakup al-hasad (dengki), al-riya’ (pamer amal), al-ujub (mengagumi dan menyombongkan diri), serta bathar (serakah), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mawlud dalam Muthahharatul al-Qulb. Al-Ghazali menegaskan bahwa keempat dosa hati ini, yang juga disebut sebagai “kejahatan hati” (khabaits al-qalb), merupakan “induk bagi sejumlah keburukan” (ummahat lijumlati mi al-khabaits) yang dapat membawa seseorang kepada kebinasaan (al-muhlikah).
Kemampuan membebaskan diri dari “dosa-dosa hati” dan dosa-dosa lainnya merupakan penanda bahwa seseorang telah memiliki kesadaran akan “keberhadiran Allah” dalam dirinya. Kesadaran ini, yang bisa dikatakan sebagai puncak pengalaman beragama, merupakan esensi ketaqwaan. Pemahaman ini mengacu pada Leopold Weiss, kelahiran Austria, yang setelah konversi menjadi Muslim berubah nama menjadi Muhammad Asad, dan menulis tafsir bertajuk The Message of the Quran, di samping buku-buku lainya. Dalam tafsirnya ini, Muhammad Asad memahami konsep taqwa sebagai “God-consciousness” atau kesadaran ilahiah, yakni kesadaran akan kemahadiran-Nya dan keinginan seseorang untuk membentuk eksistensinya berdasarkan kesadaran ini. Kondisi ini merupakan puncak keberagamaan dan keislaman seorang Muslim. Dalam al-Qur’an, surat al-Hadid, pada penghujung ayat ke-4, terdapat penegasan sebagai berikut:
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Dan Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid: 4)
Jika pada diri kita telah terbentuk kesadaran puncak tersebut, maka yang terbersit dan tampak dalam kehidupan kita sejak pada perasaan, pikiran, dan tindakan, selalu bernilai kebajikan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah. Esensi ibadah dalam Islam, sebagaimana yang juga dipahami Muhammadiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub), baik dengan cara melaksanakan “ibadah mahdhah” maupun “ibadhah ghairu mahhah”. Kualitas taqwa yang demikian, senantiasa merasakan “kehadiran Allah”, akan menghasilkan tindakan yang mengandung kebaikan, dan sebaliknya, tidak ingin mendekati perbuatan, sebagaimana disebut dalam al-Qur’an, surat an-Nahl ayat 90, yaitu: al-fahsyā’, al-munkar, dan al-baghy.
إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl:90)
Dalam Tafsir al-Munir, ketiga jenis keburukan ini diartikan sebagai berikut: “al-Fahsya’ ada;ah sesuatu yang diharamkan seperti perbuatan zina, mencuri, , menenggak minuman keras, dan mengambil harta orang lain secara batil; al-Munkar adalah apa yang dinilai buruk oleh syariat dan akal, serta perbuatan-perbuatan keji yang tampak, seperti membunuh dan melakukan kekerasan fisik tanpa hak dan alasan yang dibenarkan, menghina dan meremehkan orang lain, mengingkari dan menyangkal hak-hak orang lain; al-Baghy adalah menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak mereka.”
Hadirin Rahimakumullah
Pada tahun 1983, zaman Orde Baru, pemerintah membuat kebijakan yang disebut dengan “pengawasan melekat”, suatu pengawasan vertikal yang dilakukan atasan kepada bawahan untuk menciptakan tata kelola atau governansi pemerintahan yang efektif, efisisen, dan bersih dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada kenyataannya, KKN pada zaman Orde Baru tetap berkembang biak di semua lini dan level pemerintahan yang mengakibatkan pemerintah Orde Baru berakhir dengan al-muhlikah (kebinasaan). Setelah memegang kendali kekuasaan selama 22 tahun, rezim Orde Baru berakhir pada 1988 akibat gelombang protes kalangan masyarakat madani antara lain karena mengguritanya praktik KKN.
Setelah hampir 30 tahun lepas dari Orde Baru, praktik tersebut alih-alih berakhir, atau setidaknya berkurang, justru terjadi apa yang disebut dengan “banalisasi” KKN. KKN dianggap sebagai hal yang “biasa” atau “wajar” oleh sebagian kalangan yang memiliki posisi strategis. Belakangan ini, sekedar menyebut satu contoh saja, publik dibuat terkaget-kaget terhadap pejabat publik, yang kendati bergaji per bulan sebesar setengah miliar, toh masih mencari “tambahan” secara tidak halal yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 190-an triliuan hanya dalam 12 bulan pada tahun tertentu.
Menjamurnya praktik korupsi dalam jumlah yang sedemikian besar (mega corruption) dan massif menimbulkan kekhawatiran tata kelola pemerintahan kita jatuh pada apa yang disebut dengan “kleptokrasi”, suatu konsep yang digunakan untuk kondisi negara di mana korupsi telah menjadi budaya penguasa; atau state capture corruption, istilah internasional untuk menggambarkan situasi ketika kelompok atau aktor tertentu “menangkap” negara atau pemerintahan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok secara masif dan merasuk ke pembuatan kebijakan, undang-undang, hingga birokrasi.
Kondisi di tanah air menjadi ironi karena, meski dikenal religius dan mayoritas Muslim, keberagamaan kurang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian Profesor Hossein Askari dan Dr. Scheherazade S. Rehman (2010) dalam How Islamic Are Islamic Countries? mengukur kepatuhan 208 negara terhadap prinsip Islam berdasarkan empat sub-indeks: ekonomi, hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, serta hubungan internasional. Hasilnya, 10 negara dengan indeks keislaman tertinggi justru bukan negara Muslim, melainkan: (1) New Zealand, (2) Luxembourg, (3) Ireland, (4) Iceland, (5) Finland, (6) Denmark, (7) Canada, (8) UK, (9) Australia, dan (10) Netherlands. New Zealand, misalnya, meski hanya 1,3% penduduknya Muslim, memiliki indeks keislaman tertinggi berkat tingkat korupsi yang sangat rendah.
Hadirin Rahimakumullah
Adanya situasi yang kontras atau paradoks pada beberapa aspek kehidupan sosial kita dengan kehidupan keagamaan merupakan petunjuk penting bahwa nilai-nilai keagamaan belum terinternalisasi. Datangnya bulan Ramadhan yang dikenal juga sebagai syahrus shiyam seharusnya merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dengan pengertian taqwa yang sebenar-benarnya, yakni terbentuknya kesadaran yang kuat dan mendalam bahwa Allah merupakan zat mutlak yang senantiasa hadir dan mengawasi kehidupan kita. Praktik “memerkaya diri dan orang-orang di sekitarnya” mengindasikan masih rendahnya kesadaran ilahiah tersebut. Ketaqwaan dalam arti yang sebenar-benarnya yang melekat pada diri seseorang mengondsikan hati yang bersih (al–qalb al-salim).[1] Kondisi hati semacam inilah yang menjadi tempat meminta pertimbangan etik terhadap perbuatan yang kita lakukan, sebagaimana hadist berikut ini:
اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ
“Mintalah fatwa kepada hatimu! Kebajikan adalah apa yang menenangkan jiwa dan menenangkan hati, sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa ragu dan bimbang di dalam dada.”
Penjelasan Nabi yang disampaikan kepada Wabishah pada hadist di atas, terkandung makna yang mendalam bahwa sejatinya hati manusia merupakan sumber petunjuk kebenaran bagi setiap manusia; pemberi pertimbangan terhadap perbuatan yang buruk dan baik. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau kejahatan, sejatinya mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hati nurani, dan karena itu bertentangan pula dengan agama.
Supaya hati tetap dalam kondisi bersih atau sehat, terhindar dari hati yang sakit (al-qalb al-marid)[2], apalagi menjadi hati yang mati (al-qalb al-mayyit)[3], diperlukan suatu “lelaku” yang dilakukan secara rutin, di antaranya puasa Ramadhan. Tindakan “memerkaya diri” merupakan indikasi nyata ketamakan, salah satu penyakit hati, atau pantulan dari “hati yang sakit” (al-qalb al-marid). Puasa Ramadhan pada dasarnya merupakan sarana melatih diri untuk merasakan kehadiran Tuhan sehingga kita mencapat predikat manusia taqwa dalam pengertian taqwa yang sebenar-benarnya. Pihak yang paling tahu terhadap pelaksanaan puasa adalah pelaku sendiri dan Allah. Bisa jadi tanpa sepengetahuan orang lain, kita membatalkan puasa, lalu kita mengakui masih berpuasa. Tetapi karena memiliki kesadaran Allah sebagai “God- consciousness”, meskipun dalam kondisi haus dan lapar, puasa tetap dipertahankan hingga berbuka dan dilaksanakan selama sebulan penuh.
Latihan merasalan “kehadiran Allah” secara ruhani atau spiritual selama bulan Ramadhan perlu kita rawat dan ditransformasikan dalam keseharian di luar bulan Ramadhan. Puasa selama sebulan dalam bulan Ramadhan, menurut Abdul Qadir Jailani adalah “puasa syariat”, puasa yang terikat dengan ketentuan formalism fiqih terkait waktu dan tata caranya. Etos yang dipupuk selama bulan Ramadhan perlu ditransformasikan menjadi “etos puasa thariqat”. Kita akhiri khutbah ini dengan doa:
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ
يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ
. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ،. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمـُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمـُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ فيَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ.
اللّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ سَلاَمَةً فِى الدِّيْنِ وَعَافِيَةً فِى الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِى الْعِلْمِ وَبَرَكَةً فِى الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ.
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسلِمِين وَاجْمَعْ كَلِمَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقِّ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ.
اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاْلأَنْصَارِ
اَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَـقَـبَّلْ مِنَّا صَلاَتَنَا… وَتُبْ عَلَينَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
[1] Hati yang bersih dari segala syahwat (keinginan yang melampaui batas) dan syubhat (keraguan), hati yang tidak memiliki kehendak kecuali hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalamnya hanya ada kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada-Nya, pengharapan kepada-Nya, kembali kepada-Nya, ridha terhadap-Nya sebagai Rabb, ridha dengan ketetapan-Nya, dan tawakal kepada-Nya. ( الْقَلْبُ السَّلِيم )
وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ إِرَادَةٍ تُخَالِفُ أَمْرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَحَبَّةُ اللهِ، وَخَشْيَتُهُ، وَرَجَاؤُهُ، وَالإِنَابَةُ إِلَيْهِ، وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ.
[2] Hati yang di dalamnya ada kehidupan sekaligus ada penyakit. Ia memiliki keimanan dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya, tetapi juga diuji dengan syahwat dan keraguan. Terkadang ia tertarik kepada kebenaran, namun terkadang condong kepada hawa nafsu. Hati ini berada di antara sehat dan sakit. ( الْقَلْبُ الْمَرِيضُ )
وَهُوَ قَلْبٌ فِيهِ حَيَاةٌ وَمَرَضٌ، فِيهِ إِيمَانٌ وَمَحَبَّةٌ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنَّهُ مُبْتَلًى بِالشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ. مَرَّةً يَنْجَذِبُ إِلَى الْحَقِّ وَمَرَّةً يَمِيلُ إِلَى الْهَوَى. فَهُوَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ.
[3] Hati yang telah mati karena kekufuran, maksiat, dan kebodohan. Ia tidak mengenal, tidak beribadah sesuai perintah Tuhannya, tidak mencintai apa yang dicintai Allah, tidak membenci apa yang dibenci Allah. Hati ini hanya mengikuti hawa nafsu, tunduk kepada syahwat. Hati yang gelap, jauh dari Allah, dan menjadi tempat bagi setan. (الْقَلْبُ الْمَرِيضُ )
وَهُوَ قَلْبٌ فِيهِ حَيَاةٌ وَمَرَضٌ، فِيهِ إِيمَانٌ وَمَحَبَّةٌ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنَّهُ مُبْتَلًى بِالشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ. مَرَّةً يَنْجَذِبُ إِلَى الْحَقِّ وَمَرَّةً يَمِيلُ إِلَى الْهَوَى. فَهُوَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ.
Editor Saiful Ibnu Hamzah