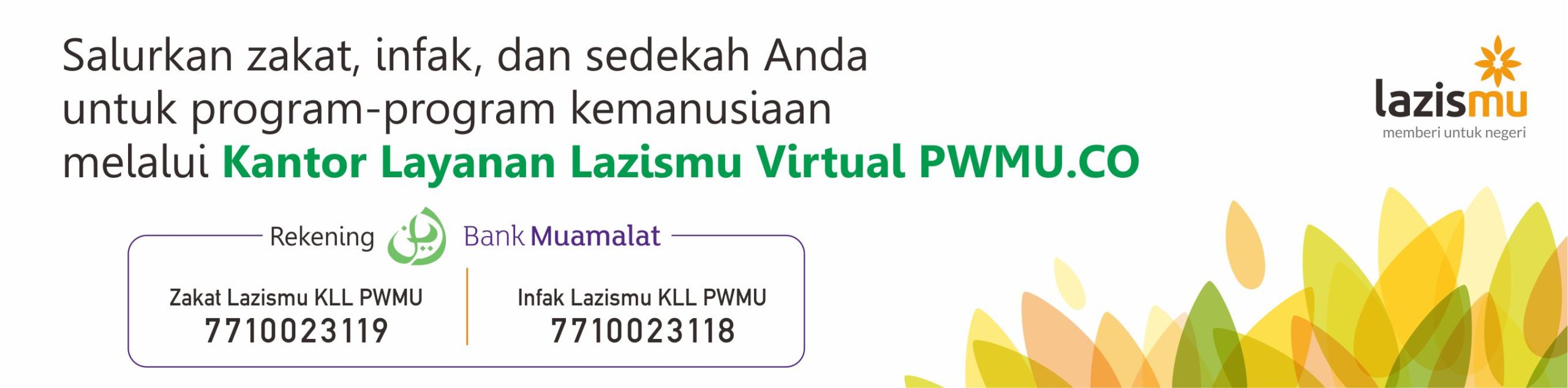Refleksi Konseptual atas Perubahan PPDB Menjadi SPMB
Oleh Dr. Piet Hizbullah Khaidir, S.Ag., MA.
Ketua STIQSI Lamongan; Sekretaris PDM Lamongan; & Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur
Diksi ‘Peserta Didik’ dan ‘Murid’ menjadi perbincangan hangat dalam sistem rekrutmen anak didik baru. Hal itu mengemuka setelah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Menteri Dikdasmen Kabinet Merah Putih pada tahun 2025 ini menetapkan perubahan nama pada sistem rekrutmen peserta didik atau murid oleh sekolah dasar dan menengah. Perubahan nama itu adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ada perbedaan cukup mendasar antara PPDB dan SMPB. Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, jalur pendaftaran PPDB meliputi: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali;dan/atau prestasi. Sedangkan jalur penerimaan SPMB meliputi: domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi. Yang berubah adalah domisili dan prestasi yang berdiri sendiri.
Poin domisili dimaksudkan berkaitan dengan jarak dan pilihan kualitas sekolah. Bukan dengan zonasi wilayah kerja administratif. Dengan konsep domisili ini, murid yang tinggal di daerah kabupaten tertentu, dan berjarak dekat dengan suatu sekolah di kabupaten lain, dapat bersekolah di sekolah tersebut. Tanpa dipengaruhi oleh kebijakan zonasi. Begitupula poin prestasi ditambahi uraian tentang keaktifan dalam organisasi dan kepemimpinan. Dimaksudkan sebagai penghargaan kepada prestasi murid yang memiliki talenta keorganisasian dan kepemimpinan, di samping prestasi akademik.
Tulisan ini tidak membahas tentang detail apa saja perbedaannya, melainkan menambahi argumen apa dan filosofi kenapa perubahan istilah dalam sistem rekrutmen tersebut penting bagi dunia pendidikan. Misalnya terkait istilah peserta didik dan murid, yang dalam kaitan sistem pendidikan, sangat menarik untuk diuraikan, terutama berkenaan dengan konsep dan relasi guru-murid, adab dan intelektualisme, dan pendidikan yang holistik.
Konsep Guru dan Murid
Di dalam tradisi pendidikan kita di Indonesia, sistem dan lembaga pendidikan biasanya menyebut guru dan murid dengan beberapa istilah. Pendidik biasanya disebut: guru, ustadz, kiai, syaikh, maulana, tuan guru, ajengan, pangersa, ayatullah dan lain-lain. Sedangkan peserta didik biasanya dipanggil: murid, siswa, santri, thalib, cantrik, abdi dalem, peserta didik, pelajar dan lain-lain. Masing-masing memiliki penekanan sudut pandang makna yang berbeda-beda.
Di sekolah umum, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan mentransfer ilmu kepada anak didiknya, biasanya disebut guru. Istilah guru ini informasinya berasal dari Bahasa Jawa. Jika benar berasal dari Bahasa Jawa, maka istilah tersebut merupakan kependekan dari digugu dan ditiru. Filosofi seorang guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, sekaligus dapat menjadi panutan yang dapat digugu (dipercaya dan dipatuhi) dan ditiru (dicontoh, diikuti, dan diteladani).
Di Pondok Pesantren, seorang yang bertugas mengabdi dan mengajar mata pelajaran, utamanya keagamaan, biasanya disebut ustadz. Kata ini berasal dari Bahasa Arab atau Persia, yang bermakna orang yang memiliki kemampuan dan kedalaman ilmu agama, dan kemudian mengajarkannya kepada santri-santrinya. Secara makna, antara ustadz dan guru memiliki kesamaan. Di Pondok, sembarang guru mengajar mata pelajaran apa saja, biasanya tetap dipanggil ustadz. Sedangkan di sekolah, seorang guru dipanggil ustadz hanya ketika sang guru memiliki keahlian di bidang keagamaan.
Makna Beberapa Istilah Terkait Guru
Di kalangan masyarakat pesantren tradisional, orang yang alim dalam bidang keagamaan, masih dibedakan penyebutannya. Maka, ada ustadz. Yang lebih tinggi lagi derajat keilmuan keagamaannya disebut kiai. Kekhususan lainnya antara seorang ustadz dan kiai dalam masyarakat pesantren tradisionalis adalah ustadz tidak memangku pesantren. Sedangkan seorang ustadz disebut kiai ketika dia merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren, dengan ciri khas mengimami shalat rawatib dan mengajar kitab turath.
Yang lebih menarik, di Saudi Arabia, dan pada umumnya tradisi sunni, istilah ustadz merujuk gelar akademik tertinggi yaitu doktor. Di atasnya lagi adalah profesor yang biasanya disebut syaikh. Sementara itu, dalam tradisi Iran yang syi’i, penyebutan guru biasanya dengan empat tahap: S1 disebut ustadz; S2 digelari hujjat al-Islam, sedangkan S3 dijuluki ayatullah. Terakhir, ketika seorang ayatullah telah menjadi marja’ (referensi utama), dia akan dipanggil dengan ayatullah al-‘uzma, serupa syaikh atau profesor.
Di dalam tradisi daerah lain, istilah guru memiliki gelaran nama julukan yang berbeda pula. Misalnya, tuan guru (Nusa Tenggara Barat), maulana (alumni India atau Pakistan yang tergabung Jamaah Tabligh), ajeungan dan pangersa (dua istilah yang sepadan dengan istilah kiai dalam tradisi pondok pesantren di Jawa Barat).
Hal yang penting menjadi catatan adalah bahwa keseluruhan nama dan istilah yang merujuk kepada makna guru di atas, pernah menjadi murid, bukan sekedar peserta didik. Mereka pernah menjadi santri, bukan sekedar siswa; menjadi abdi ndalem kiai, bukan sekedar thalib; Mereka pernah menjadi cantrik kiai, bukan sekedar pelajar.
Capaian Derajat Guru
Mereka bisa mencapai derajat guru, ustadz, tuan guru, kiai, maulana, ajeungan, pangersa, ayatullah, karena ketika menjadi murid terlibat begitu intens dalam ketaatan, pengabdian (ngawula), dan ikhlash. Mereka benar-benar menjadi santri yang jiwa raganya hanya untuk belajar dan mengabdi di jalan ilmu. Bukan sekedar sebagai pelajar dan peserta didik yang dalam belajar bersifat administratif, mengejar nilai angka di rapor, serta tidak melibatkan dirinya dalam pengabdian kepada ilmu dan guru.
Pendek kata, ini adalah soal adab dan sopan santun dalam membangun relasi dengan guru. Adab dan sanad ilmu dalam keridhaan seorang guru yang terjaga dalam hati yang jernih, bersih, dan tanpa prasangka. Adab dan akhlak terpuji seorang murid ketika berhadapan dengan gurunya di kelas, di jalan, atau di majelis ilmu lainnya. Inilah yang penting sebagai refleksi konseptual dalam makna murid dan peserta didik dalam konteks relasi guru murid dan keilmuan. Dalam konteks adab dan intelektualisme.
Adab dan Intelektualisme
Kita terkaget-kaget menyaksikan sebuah video, beberapa peserta didik terlibat dalam pengeroyokan terhadap gurunya. Dipukul dengan gagang sapu. Ditendang. Ditinju. Tanpa ada rasa dosa, apalagi kekuatiran akan masa depannya. Mau dipertaruhkan dan diperjaminkan dengan apa keberkahan hidup peserta didik durhaka itu kelak di masa depan di dunia ataupun di akherat, ketika terhadap gurunya tidak ada lagi sopan santun, bahkan lebih tragis berlaku dengan kekerasan.
Tidakkah mereka belajar dari guru-guru sebelumnya, yang mencapai derajat keilmuan karena memosisikan dirinya sebagai murid yang ikhlash, taat, patuh, dan menjaga hatinya dengan penuh khidmah mengabdi di jalan ilmu. Sungguh, dalam sejarah kenabian, dalam relasi Nabi Muhammad Saw., dan para sahabatnya, dalam relasi guru-murid di kalangan tabi’in, dan tabi’it tabi’in, keseluruhannya dibangun dalam bingkai adab dan intelektualisme. Pada adab yang terjaga itu, tumbuhlah keberkahan, kebaikan, dan kemajuan. Pada adab yang terjaga itu, lahirlah intelektualisme abadi sepanjang zaman. Lihatlah, bagaimana abadinya ilmu Imam Jakfar Shadiq, ilmu Imam Abu Hanifah, ilmu Imam Malik, ilmu Imam al-Syafi’i, ilmu Imam Ahmad, ilmu Imam Ghazali, ilmu Imam Fakhr al-Din al-Razi, ilmu khatam al-auliya’ Syaikh Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi, ilmu sulthan al-auliya’ Syaikh Abd al-Qadir al-Jilani, dan lain-lain.
Saya ingin memberikan contoh agak lompat secara zaman dalam kaitan adab dan intelektualisme ini. Kisah tentang Imam Muhammad Idris al-Syafi’i terhadap gurunya, Imam Malik. Dua hal patut dicatat terkait adab dan intelektualisme Imam al-Syafi’i. Pertama, Imam al-Syafi’i ketika menjadi murid Imam Malik tidak pernah datang terlambat ke majelis ilmu gurunya itu. Kedua, di Majelis Imam Malik, Imam al-Syafi’i yang duduk paling depan, ketika membuka buku tidak pernah dilakukan dengan kasar sehingga menimbulkan bunyi. Ketika ditanya, kenapa membuka buku dengan pelan, jawab Imam al-Syafi’i: “Karena Aku tidak ingin perbuatanku dapat mengganggu kekhusyu’an Imam Malik mengajar.”
Penutup: Pendidikan Holistik
Kontras dengan akhlak para ulama yang adab dan intelektualismenya terjaga, bolehlah kita bertanya: Apa yang terjadi dengan pendidikan dan sistem pendidikan kita, sehingga melahirkan peserta didik yang beringas? Apakah falsafah makna yang melekat pada peserta didik membuat mereka kurang memiliki kesadaran untuk belajar dengan ikhlash, hati yang jernih dan jiwa-raga yang siap berkhidmah di jalan ilmu? Sepertinya kita membutuhkan suatu sistem yang dimulai sejak dini, dengan mengenalkan pendidikan yang sifatnya holistik.
Akhirul kalam, kebijakan Mas Menteri Dikdasmen mengenalkan dan membiasakan 7 kebiasaan anak hebat, deep learning, dan terakhir pengubahan nama PPDB menjadi SPMB dapat menjadi fondasi penerapan pendidikan holistik. Pendidikan yang benar-benar fokus untuk mengajarkan adab dan sopan santun, serta laku intelektualisme yang menjadi tujuan utama pendidikan nasional Indonesia. Mudah-mudahan setelah penerapan kebijakan Mas Menteri berjalan dengan baik dan berhasil, lahirlah ulama cendekiawan yang mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan dan kemaslahatan bangsa Indonesia lahir batin, dunia akherat. Aamiin. Wallaahu a’lam.