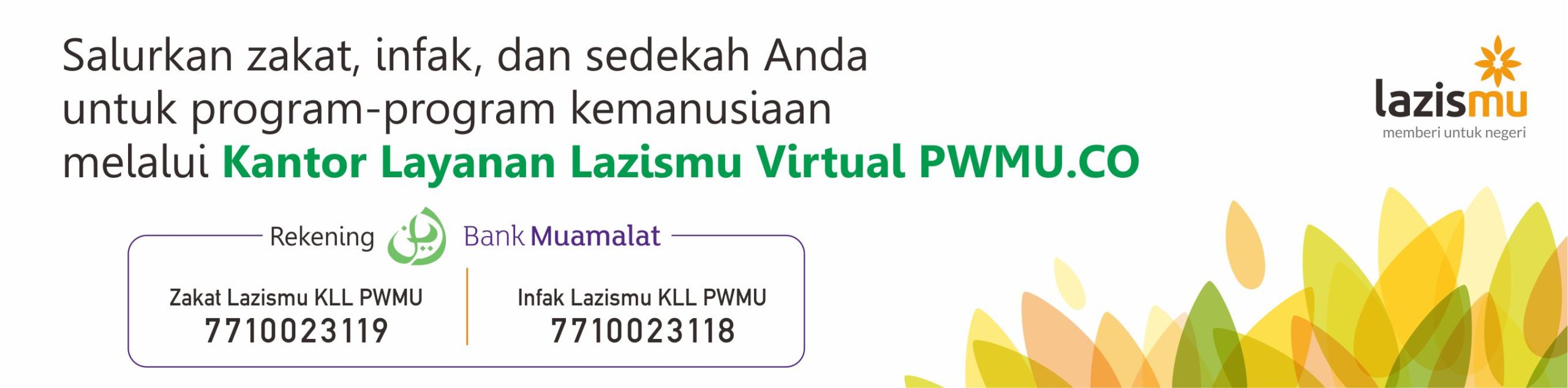Oleh Dr. Piet Hizbullah Khaidir, MA.
Ketua STIQSI Lamongan, Sekretaris PDM Lamongan dan Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur
Syahdan seorang sufi yang wara’ dan ‘alim setelah membaca hamdalah malah merasa bersalah. Sehingga, atas perasaan bersalahnya tersebut, selama 30 tahun, sang sufi memohon ampunan Allah Swt., melalui istighfar yang tiada henti. Dikisahkan bahwa dalam sebuah peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di pasar di kota dia tinggal, tokonya adalah satu-satunya toko yang tidak terbakar. Sang sufi, ketika peristiwa naas itu terjadi, sedang tidak berada di kota tempat tinggalnya itu. Di tengah jerit tangis tetangga-tetangganya, dia baru saja kembali, sambil bertanya-tanya dan mencari tahu apa yang terjadi.
Ketika dia akhirnya mengetahui musibah yang menimpa pasar di kotanya, dia langsung menuju tokonya, dan spontan mengucap hamdalah, sebagai rasa syukur, karena tokonya selamat dari lumatan api. Ketika tersadar hamdalahnya mengundang mata yang dibalut kesedihan menatapnya penuh dengan kode kesenduan, batinnya berbisik “Ya Tuhan, aku telah mengucap kesalahan dengan memuji-MU. Aku seolah telah mensyukuri musibah yang menimpa saudara-saudaraku. Aku tidak peka, karena seolah menari di atas penderitaan orang-orang yang telah tertimpa musibah.” Dapatlah rasa syukur sang sufi ini disebut dengan paradoks hamdalah.
Al-Saqati: Sang Sufi
Siapakah sang sufi yang memiliki kesadaran tentang paradoks hamdalah tersebut? Nama lengkapnya Sarī ibn al-Mughallis al-Saqaṭī (155-253 H atau 772-967 M), yang biasa dikenal dengan nama Sarī al-Saqaṭī saja. Guru tasawuf yang memiliki pengaruh spiritual pada zamannya dan zaman sesudahnya. Beliau berguru di antaranya kepada Ma’ruf Karkhi, dan berpengaruh terhadap sufi besar Baghdad, Junayd al-Baghdadi. Beliau dijuluki al-Mughallis karena tidak keluar rumah kecuali hanya untuk beribadah.
Dalam tradisi tasawuf ada dua pandangannya yang terkenal: Pertama, dalam melaksanakan tradisi tasawuf tidak boleh meninggalkan syari’at. Tidak bermakna tasawuf yang fokus kepada keramat sufi, sementara meninggalkan shalat dan syari’at lainnya. Kedua, sebelum belajar tasawuf, sebaiknya perdalam terlebih dahulu al-Qur’an dan hadits.
Hamdalah dan Realitas Paradoks
Dalam realitas sosial dan mu’amalah kita sehari-hari, seringkali terjadi paradoks hamdalah ini. Maka, pertanyaan berikut dapat dijadikan pintu masuk memahami paradoks hamdalah itu. Apakah ketika ingin bersyukur kepada Allah, kita perlu menyaksikan penderitaan orang lain terlebih dahulu baru kemudian mengucap hamdalah? Misalnya, setelah melihat penderitaan dan musibah menimpa orang lain, kita serta-merta terdorong untuk mengucapkan hamdalah, karena kita tidak mengalaminya. Merasa bersyukur dan paling dekat dengan Allah, sehingga kita dijauhkan dari musibah, sementara orang lain banyak dosa dan jauh dari Allah, lalu tertimpa musibah.
Bersyukur merupakan perbuatan lahiriah dengan ucapan hamdalah melalui lisan kita. Pada saat yang sama, bersyukur juga merupakan perbuatan batiniah dengan hati yang tunduk merasakan diri sebagai hamba Allah Swt. Harus jalin berkelindan antara bersyukur lahiriah dan batiniah. Sejatinya, jalin kelindan syukur lahiriah dan batiniah terhubung dalam laku kehalusan hati bahwa niat hamdalahnya untuk tujuan apa.
Dalam tradisi yang menjadi realitas sosial budaya yang berkembang di masyarakat berbahasa Indonesia dan Jawa, ungkapan syukur berimplikasi pada makna-makna yang unik, dan bahkan lepas dari makna bersyukur itu sendiri, dan terkadang bersifat negatif. Ungkapan “Syukurin, Lu”, adalah ungkapan syukur yang dipergunakan untuk menyumpahi secara sarkas penderitaan yang telah dialami oleh seseorang yang mungkin menyebalkan atau susah diberi nasehat. Maka, ketika sebuah nasehat yang seharusnya diikutinya, tidak diindahkan, dan musibah yang bertolak-belakang dengan nasehat itu terjadi pada seseorang tersebut, ungkapan syukurin Lu tadi menjadi sarkas.
Sementara itu, ungkapan “Syukur cuma luka di tangan, tidak sampai sekujur tubuh” adalah ungkapan cara bersyukur masyarakat dengan tradisi Bahasa Jawa yang dinarasikan sebagai bentuk nrima musibah yang sedang terjadi atau dialami. Daripada ngersula. Lelaku nrima ini memang khas khususnya Masyarakat Jawa, atau boleh dikatakan Masyarakat berbahasa Indonesia pada umumnya. Syukur sebagai nrima ini bernilai positif jika diikuti oleh upaya berhati-hati agar tidak terjadi hal serupa.
Paradoks penggunaan kata syukur terjadi di sini. Syukur yang seharusnya menjadi ungkapan hamdalah untuk memuji hanya kepada Allah Swt, justru dipergunakan untuk nyumpahi musibah yang menimpa orang lain. Maka, laku kehalusan hati memang sudah seharusnya menjadi tolok ukur hamdalah, agar tidak terjadi paradoks. Laku kehalusan hati dalam bersyukur mengekspresikan rasa syukur dengan tepat waktu, tempat dan sasarannya. Seperti yang dilakukan sufi agung di atas, dia mengoreksi hamdalahnya yang tidak tepat dengan istighfar.
Poinnya: hamdalahmu jangan menyakiti. Hamdalah sebagai kebaikan dengan memuji Allah Swt., tetapi dalam kasus Sari al-Saqati, seolah hadir menjadi ketidakpekaan syukur, karena mensyukuri nikmat hanya untuk dirinya, di tengah penderitaan orang lain. Yang lebih paradoks adalah kita terdorong mengucap hamdalah, hanya karena menyaksikan orang lain tertimpa musibah, sementara kita selamat dari musibah.
Mengucap hamdalah karena kita tidak tertimpa musibah, tanpa kepekaan di depan orang yang tertimpa musibah bukanlah hamdalah yang tepat, bukanlah hamdalah yang benar, dan bukanlah hamdalah yang tepat sasaran. Sebaliknya, merasakan kesedihan mendalam atas musibah yang dialami orang lain, membantunya sedapat mungkin untuk meringankan bebannya, adalah bentuk syukur terbaik.
Menghindari Paradoks Hamdalah
Agar tidak terjadi paradoks hamdalah, maka hamdalah perlu dimaknai dan diimplementasikan sebagai refleksi diri bahwa segala puji hanya untuk Allah. Bukan untuk selain-Nya, bukan untuk kepentingan yang sifatnya eksternal. Bukan untuk tujuan keuntungan diri sendiri karena merasa memperoleh nikmat dari Allah. Maka, memuji Allah dengan hamdalah dengan ungkapan berikut ini bukanlah hamdalah sejati. Hamdalah yang berfungsi untuk keuntungan diri sendiri. Hamdalah yang ditujukan bukan untuk memahami rahasia Keputusan Allah.
Bentuk ungkapannya begini: “Ya Allah, alhamdulillah Engkau karuniai aku dan keluargaku dengan anak-anak yang shaleh, cerdas, dan tidak cacat. Tidak seperti keluarga si A itu yang Engkau karunia anak yang nakal, cacat, dan bodoh”. Sungguh, hamdalah tersebut adalah contoh paling nyata dari paradoks hamdalah. Ini adalah paradoks hamdalah dalam lirih doa.
Mengucap doa dalam lirih paradoks hamdalah sudah menyakitkan, apalagi ketika diucapkan di hadapan orangnya langsung. Misalnya, di hadapan orang jomblo yang sepertinya susah untuk segera mendapatkan jodoh kita berkata begini: “Alhmadulillah pulang liburan kemarin, aku sudah mendapatkan restu dan lampu hijau dari orang tuaku untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius”. Atau ucapan ini di hadapan orang yang sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan: “Alhamdulillaah adikku yang tahun lalu menikah, sekarang sedang isi, baru jalan 8 pekan”. Sungguh paradoks hamdalah ini terlalu menyakitkan.
Untuk menghindari paradoks hamdalah, kita perlu memahami hamdalah dengan baik dan benar. Hamdalah yang baik dan benar adalah hamdalah yang dapat melahirkan isim tafdhil ahmad (orang yang terpuji); membentuk isim maf’ul mahmud (orang yang dipuji karena kemurahannya secara individual) yang berasal dari wazan fi’il tsulatsi mujarrad hamada; dan menghadirkan pencerahan isim maf’ul muhammad (orang yang terpuji karena akhlak dan kemurahannya yang terorganisir secara sistematis) yang berasal dari wazan fi’il tsulatsi mazid bi harf wahid ahmada.
Penutup: Hamdalah Segala Puji Hanya Untuk Allah
Hamdalah adalah hamdun dan syukur. Dua makna yang saling jalin berkelindan dan saling melengkapi. Hamdun itu ungkapan syukur yang hanya khusus untuk Allah, ditujukan kepada Allah, dan dipersembahkan untuk Allah semata. Sedangkan syukur adalah makna ungkap terima kasih yang dapat tertuju kepada Allah dan juga manusia. Oleh karena itu, hadits Nabi Muhammad Saw., menegaskan tentang hal ini: “Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah.” Ketika kita memperoleh kebaikan dari orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah.
Yang menarik adalah ungkapan dalam Bahasa Arab dalam penghujung dialog, ketika seseorang diberi sesuatu atau kebaikan, dia akan mengatakan syukran, dan yang memberi menjawab ‘afwan. Rahasia lafal ‘afwan di dalam ucapan balasan atas terima kasih yang dilontarkan dalam Bahasa Arab adalah bahwa memberi itu kewajiban. Sebagai kewajiban, dikuatirkan Allah tidak ridha. Oleh karena itu, ucapan ‘afwan sejatinya adalah permohonan maaf kepada Allah dengan penuh rasa takut (khawf) ketika melakukan pemberian kurang tepat di mata Allah.
Sebelum penutup, ijinkan penulis mengutip ungkapan penulis sastra, Ibrahim Muhammad Hasan al-Jamal, yang bersyair: Jangan memberi untuk dipuji, dan jangan memuji untuk diberi (laa tu’thi li tumdah, wa laa tamdah li tu’thaa).
Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mengimplementasikan hamdalah sejati. Hamdalah tanpa paradoks. Semoga kita semaksimal mungkin dapat terhindar dari paradoks hamdalah. Aamiin. Wallaahu a’lam.