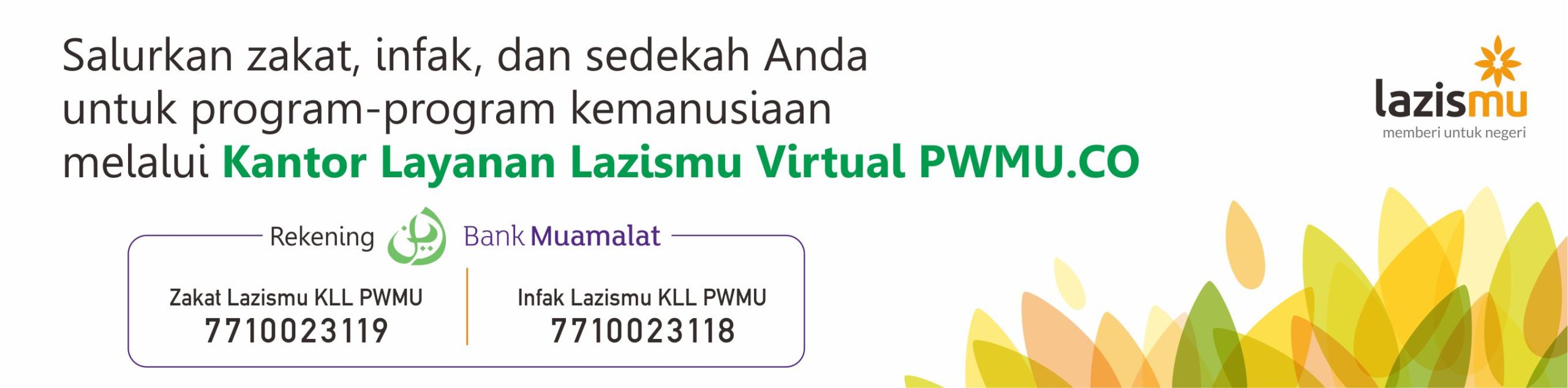Mengubah Pendapat Bukan Aib
Kita harus memahami bahwa merevisi dan mengubah pendapat itu bukanlah sebuah aib, dan tidak akan menjatuhkan kredibilitas keilmuan ulama tarjih karena sebagaimana yang telah digariskan dalam pokok manhaj tarjih bahwa yang paling mendasar bagi Muhammadiyah adalah dalil, landasan berpikir dan sudut pandangnya yang tepat.
Ulama-ulama besar juga melakukan hal yang sama. Disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Al-Jarh wa al-Ta’dīl karya Ibnu Abi Hatim tentang sikap bijak imam Malik yang merevisi hasil ijtihadnya. Sebuah riwayat dari Ibnu Wahb menyatakan bahwa beliau mendengar Imam Malik memfatwakan tidak perlu menyela jari-jari kaki di dalam wudhu maka orang-orang (pengikutnya) setelah itu meninggalkannya (tidak menyela jari kaki dalam wudhu karena ikut pendapat imam Malik).
Kemudian Ibnu Wahb memberitahu beliau tentang sebuah riwayat dengan sanad yang shahih bahwa nabi menyela jari-jari kakinya dengan jari manisnya. Sejak itu Imam Malik mencabut fatwanya dan memerintahkan pengikutnya untuk mengamalkan hadis tersebut.
Begitu pula dengan imam Syafi’i yang sering kita jumpai melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga dapat ditemukan di dalam literasi madzab Syafi’i istilah populer qawl qadīm(pendapat lama) dan qawl jadīd (pendapat baru).
Ibnu Abidin di dalam Hāsyiyah alā al-Bahr al-Rā`iq juga menukil ungkapan imam Abu Hanifah: kita ini manusia yang sangat mungkin hari ini kita mengatakan A, besok kita merevisinya dan mengatakan B.
Perilaku para ulama besar tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa ketika pengamalan ajaran agama itu dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah terhadap dalil-dalinya maka perubahan pandangan itu menjadi wajar dan niscaya.
Ingatlah bahwa Muhammadiyah pernah merevisi fatwanya tentang hukum menggantung foto KH Ahmad Dahlan, merevisi fatwa tentang hukum api unggun dalam perkemahan HW, dalam hal penetapan awal bulan Muhammadiyah sempat berpatokan kepada imkānur rukyah sebelum berpendapat dengan wujūd al-hilālseperti saat ini. Paling mutakhir putusan tarjih menambah 8 menit untuk waktu shubuh dari ketentuan sebelumnya.
Ra’yī shawāb yahtamilu al-khatha’, wa ra’yu ghayrinā khataha’ yahtamilu al-shawāb (pendapat saya benar meskipun ada kemungkinan salah, sedangkan pendapat mereka salah meskipun ada kemungkinan benar). Ungkapan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi’i, yang dengan jelas menyatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengklaim kebenaran mutlak atas pendapatnya karena sebagaimana yang juga dikatakan oleh imam Malik bahwa aktsaru ahkām al-fiqhi mabniyyun ‘alā al-dzann (mayoritas hukum fikih diputuskan atas dasar kebenaran asumtif yang tidak mulak 100 persen. Muhammadiyah pun demikian sehingga ungkapan manhaj tarjihnya berbunyi Muhammadiyah tidak menganggap pendapatnya paling benar.
Sebenarnya prinsip ini sudah dipedomani sejak tahun 1936 dalam Penerangan tentang Hal Tardjih yang menyatakan bahwa “Kepoetoesan tardjih moelai dari meroendingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, jakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe”.
Selain menyatakan tingkat kebenaran putusannya yang tidak mutlak, narasi lengkap manhaj tarjih terkait juga mengembangkan semangat toleransi. Artinya meskipun Muhammadiyah meyakini kebenaran putusannya dan memedomaninya tetapi Muhammadiyah tidak pernah menegasikan pendapat yang lain dan tidak pernah menyalahkannya.
Manhaj tarjih ini pun mengembangkan semangat keterbukaan. Ketika gerakan ijtihad digelorakan kembali maka Muhammadiyah dengan sadar membuka diri untuk dikritisi bahkan Muhammadiyah pun siap mengubah putusannya apabila ditemukan dalil dan argumen yang dipandang lebih kuat dari pendapat dan argumen majelis tarjih yang semula.
Termasuk yang saat ini dilakukan oleh Prof Dr Zainuddin MZ dengan program literasi ketarjihan HPT Format Baru juga sedang mengajari kita tentang fleksibikutas dan kenisbian kebenaran yang pernah diputuskan, serta mengembangkan semangat toleransi dan keterbukaan.
Karakter ketarjihan inilah yang seharusnya membuat bangga warga muhammadiyah dengan memedomani putusan-putuMan tarjih dalam keseharian ibadah dan muāmalahnya. Dan dengan inilah Muhammadiyah mengembangkan cara beragama Islam yang autentik karena bukan lagi tentang gengsi organisasi tetapi tentang dalil yang menjadi pijakannya dalam beragama. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni